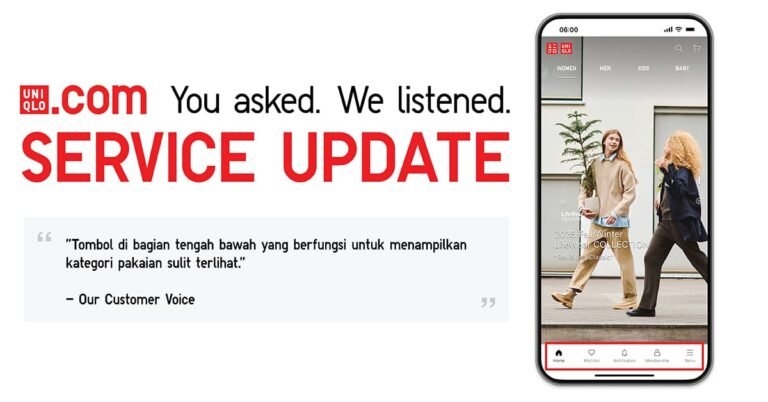(catatan: seorang petugas yang malas mencatat.)
VakansiInfo – Gue masuk dinas siang, jam dua sampai jam sembilan malam. Biasanya, gue datang lebih awal. Rokok dulu, duduk sebentar di teras mushola, baru mulai kerja. Tapi hari itu beda. Rokok pun nggak enak. Gue masuk toilet cuma buat ngelipet baju, ngumpetin seragam yang kusut, terus duduk sebentar, tapi hati tetep kosong.
Pas turun dari kereta, gue jalan di peron Stasiun Klender Baru. Di ujung sana, gue liat dua sosok yang udah lama jadi tembok terakhir kewarasan gue: Bang Ronny dan Bang Musa. Mereka bersandar di besi batas aman perlintasan PNP. Gue salamin mereka.
“Lu berdua masuk shift pagi ya, Bang?”
“Iya dong,” jawab Bang Ronny dengan semangat khas dia.
“Lu kenape, Dih? Muka lu kusut amat,” celetuk Bang Musa.
Gue nggak jawab. Gue cuma diem, nyebrang, mau masuk ruangan. Tapi langkah gue ditahan.
“Eit, sini dulu. Mau mati? Itu ada kereta mau lewat!” suara Bang Ronny.
Gue masih diem. Muka masih neges. Tapi di balik sikap ngeselin dia, gue tahu: barusan, nyawa gue baru ditarik balik. Sekejap gue ngerasa kaget sendiri, seolah ada tangan tak terlihat narik gue dari tepi jurang.
Masuk ruangan, gue cuma naruh tas. Abis itu balik lagi ke tempat mereka jaga. Tanpa nyapa siapa pun. Langsung nyender di besi peraduan—batas penyebrangan itu. Tempat yang biasanya jadi garis batas buat jaga keselamatan orang. Sekarang jadi tempat buat nahan kepala gue sendiri supaya nggak meledak.
Bang Musa berdiri di samping gue. Tangannya ngerangkul bahu gue.
“Jangan bete-bete lah, kawan. Santai aja.”
Gue senyum. Kusut. Tipis. Sepatu gue nendang-nendang pasir yang nggak jelas. Di seberang, Bang Ronny lagi ngatur penumpang… atau lebih tepatnya nggodain PNP. Kayak biasa.
Wuuuuzzzz… kereta melaju kencang. Dan Bang Ronny langsung ngelakuin reka adegan—seolah-olah dia kebawa hembusan angin kereta. Gue dan Bang Musa ketawa.
“Si Ronny udah gila ya, Di?”
“Iya iya, Bang… kayaknya dia belum minum obat cacing, dah.”
Dan di detik itu… jiwa gue balik. Bukan karena masalah gue kelar. Bukan karena gue kuat. Tapi karena ada orang-orang yang bikin gue inget, hidup bukan selalu soal beban—kadang cukup soal tawa yang bisa lo curi di sela hancurnya hari.
Gue keluarin duit sepuluh ribu. “Bang, nih buat gorengan.”
Bang Ronny senyum. Bang Musa lempar balik sepuluh ribu juga sambil ngomong:
“Tuh Ron, si Hadi mah bae, nih.”
“Liat nih, Di, gue tangkep gaya Hanamichi Sakuragi.”
Kami bertiga ketawa. Bukan tawa orang bahagia. Tapi tawa orang yang masih hidup, walaupun keadaannya nggak bikin senyum.
Dan mungkin… itu semua yang gue butuhin hari itu. Bukan solusi. Bukan pelukan. Cuma jadi bagian dari tawa receh yang nggak minta lo kuat, cuma minta lo hadir.
Tapi sayang… mereka harus turun dinas. Dan gue harus kembali sendiri.
Ruang jadi sepi lagi. Tawa hilang. Dan luka itu… masih ada di tempat yang sama, nunggu balik lagi ke permukaan. Gue diem. Karena satu-satunya yang bisa gue lakuin adalah bertahan. Bertahan sampai tawa berikutnya datang lagi entah kapan.

Muhammad Haadi Nur Haq (Acil)
Lahir di Jakarta, 12 Desember 1990. Tumbuh di keluarga sederhana namun berkecukupan, rumahnya selalu dipenuhi canda dan tawa. Sejak kecil, Acil suka mengamati dunia dari sudutnya sendiri, mencatat hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Kini, ia menulis untuk menghadirkan cerita yang hangat, penuh humor, dan mudah dinikmati pembaca—sesekali dengan sentuhan kejenakaan yang bikin senyum tipis atau setidaknya mengangguk sambil bilang, “Iya, gue ngerti nih.”