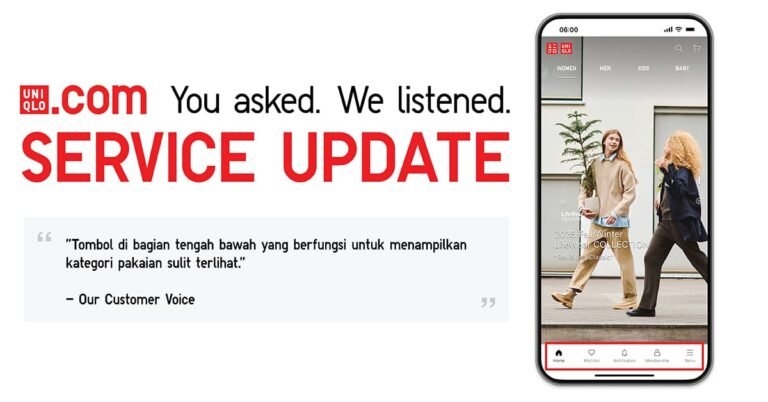Vakansiinfo – Bang Cay lagi sibuk megang kendali. Posisi Passenger Service, dia jaga di gate sambil nge-handle tiga orang dari penyedia jasa angkutan online yang minta izin masuk ke Stasiun Klender Baru. Gayanya formal, tapi gue yakin—mata sama pikirannya mungkin juga lagi pecah fokus.
Sementara itu, gue berdiri di pos perlintasan penyebrangan PNP, pegang HT dan barikade. Hari itu, gue serasa lagi cosplay jadi petugas PKD. Serius, tapi sambil nahan ketawa sendiri.
“Tahan, Bang. Jangan masuk dulu. Satu timur, dua barat mau masuk.”
Gue tutup akses pakai barikade… atau lebih tepatnya, badan gue sendiri. Walaupun kecil, tangan gue panjang—lumayan lah buat ngehalangin maling kali ah.
Mata gue sesekali nengok ke kiri kanan, tapi lebih banyak mantau ke arah depan—ngeliat Bang Cay yang lagi ngobrol sama tiga perempuan tadi. Satu orang tampak lebih dewasa, berjilbab, kelihatan sopan dan kalem. Dua lainnya lebih muda, penampilan rapi dan stylish, pakai seragam khas—entah celana span atau rok span, gue nggak ngerti namanya.
Gue sempat nyengir sendiri. Bukan karena aneh-aneh, tapi karena suasananya absurd aja. Tengah hari bolong, kereta lalu-lalang, dan di tengah panas itu muncul tiga orang asing kayak iklan rekrutmen.
“AWAS JALUR SATU MELINTAS!”
Wuuuuzzz… satu kereta lewat. Barikade masih gue tahan.
Dari seberang, Bang Roelz nyeletuk, “Tahan, Di!”
Disusul Ade Bibir, “Minta nomor HP-nya dulu baru masuk!”
Gue langsung kasih kode: jari telunjuk nempel ke bibir. Kita semua paham artinya. Becandaan klasik anak perlintasan.
Setelah gate dibuka, Bang Cay nyamperin gue. Nyender santai, gaya abang-abangan yang udah kenyang panas-panasan.
“Dari tiga tadi, lu pilih yang mana, Di?”
Gue nyengir dikit.
“Yang paling kiri lah, Bang. Mukanya manis, mirip artis FTV jam 11 malam.”
Bang Cay ketawa kecil.
“Kalau gak inget anak bini mah, beuh… yang hijab udah gue ajak ngopi sore tuh.”
“Jangan diajak ngopi, Bang. Emangnya itu teman SMA?”
“Ah, Saleep… salah gue ngomong sama orang kayak lu.”
Kami ketawa kecil. Di balik debu, panas, dan suara klakson kereta, momen-momen kayak gitu yang bikin stasiun berasa rumah.
Gak lama, Jaelani dateng. Partner kerja gue di shift berikutnya. Gue liat jam.
“Oh iya, udah jam dua.”
“Sorry, Bang Hadi. Gue telat.”
“Santai, Jay.”
Tim aplusan mulai briefing.
Dan buat gue, hari itu bukan cuma pergantian shift. Itu hari terakhir. Besok, nama gue udah gak tercantum di jadwal.
Gue masuk ke ruangan. Rame. Tapi suara-suara itu cuma lewat di telinga. Rasanya kayak sendirian di tengah pasar. Tau lalat kalau lagi ngerubungin bangke? Kira-kira gitu situasinya. Semua cowok lagi ngumpul, mantau tiga perempuan tadi yang sekarang duduk manis—nunggu giliran buat ditanya sebelum lanjut dinas.
Masuklah… Cang Hamdi. Sang jenderal gaya bebas.
Dengan suara khasnya, dia buka percakapan:
“Jadi, mba-mba ini dari pihak penyedia jasa angkutan online, ya. Yang dua ini petugas baru, gantiin mba yang satunya lagi.”
“Satu bakal tugas di Klender Baru, satu lagi di Cakung.”
“Yaudah, tunggu sini dulu ya. Di, lu ajak ngobrol dulu yak…”
Dan gue yang ditunjuk. Lah buset. Padahal lagi asik buka COC sambil ngerokok. Gue bengong. Dalam hati: Waduh, bareng sama gue dong. Tapi besok gue libur sih…
“Iya, Pak,” jawab salah satu dari mereka.
“Pak,” katanya. Waduh. Berasa banget tuanya. Gue celetuk,
“Panggil Opung aja.”
Semua ketawa. Termasuk si mba yang dari tadi gue perhatiin. Dan ternyata… dia yang bakal dinas di Cakung. Yang dari tadi gue becandain sama Bang Cay. Ketawanya malu-malu, tapi manis. Sepet gimana gitu liatnya.
Godaan tuh gak harus digodain. Tapi kalau udah nongol depan mata… susah juga nolaknya.
Gue iseng nanya,
“Eh, bocah-bocah PKD udah mulai nyiapin acara nanti malam belum?”
Soalnya malam itu… rencananya jadi malam terakhir gue di situ.
Gak lama, Cang Hamdi balik lagi, dan ngasih izin ke ketiga perempuan itu buat lanjut ke Stasiun Cakung.
Gue juga pamit. Mata berat. Ngantuk.
“Bang, nanti malam jam sembilan-an gue balik ke sini lagi, ya.”
“Siap, Di. Gue tunggu, yak. Awas lu kalau gak dateng!”
Gue cuma angkat jempol. Jalan pelan keluar stasiun. Tapi kepala gue penuh pertanyaan.
Gue gak pernah benar-benar sadar kapan semuanya mulai berubah.
Tapi kayaknya… jauh sebelum surat tugas itu turun, Stasiun Klender Baru udah mulai ngelepasin gue pelan-pelan. Bukan lewat pengumuman. Bukan lewat kata-kata. Tapi lewat sinyal-sinyal kecil… yang cuma bisa dirasain sama orang yang bakal ninggalin sesuatu yang penting.
Suara peron yang biasanya rame, mulai kedengeran kayak bisik-bisik pamitan. HT yang biasanya nyaring, sekarang kayak ngerem suaranya sendiri. Langkah kaki penumpang yang gue lihat tiap hari… tiba-tiba terasa kayak langkah orang-orang yang bakal gue kangenin.
Gue masih ketawa sama Bang Cay dan Roelz. Masih ngopi. Masih becandain tiket nyasar dan ibu-ibu yang bingung arah.
Tapi di dalam kepala, gue udah mulai nyusun satu kalimat yang paling sulit buat gue ucapin:
“Gue bakal pergi.”
Dan anehnya… waktu gue akhirnya pergi beneran, gak ada yang berubah terlalu drastis. Gak ada pelukan. Gak ada tangis.
Cuma satu candaan, satu ejekan, satu kartu pass gate yang dikasih balik… dengan gaya ancaman penuh sayang:
“Gue gak mau kenal sama lu ya, Di, kalau gak balik ke sini.”
Itu aja cukup. Karena kadang… perpisahan paling berat tuh gak perlu dibilangin. Dia cuma datang… dalam bentuk tawa yang hening, dan mata yang gak berani saling liat terlalu lama.
Dan yang pasti…
Gue bakal kangen bakso Pakde. Yang tiap siang mangkal di bawah flyover itu—flyover yang dulunya perlintasan sebidang, sumpek, macet, dan panas.
Tapi di balik riuhnya kendaraan yang lalu lalang, bau kuah bakso, dan deru motor yang nunggu palang pintu itu, gue nemu satu hal sederhana yang bikin berat buat ninggalin:
Kehidupan yang gue jalani tanpa sadar… udah gue anggap rumah.

Muhammad Haadi Nur Haq (Acil)
Lahir di Jakarta, 12 Desember 1990. Tumbuh di keluarga sederhana namun berkecukupan, rumahnya selalu dipenuhi canda dan tawa. Sejak kecil, Acil suka mengamati dunia dari sudutnya sendiri, mencatat hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Kini, ia menulis untuk menghadirkan cerita yang hangat, penuh humor, dan mudah dinikmati pembaca—sesekali dengan sentuhan kejenakaan yang bikin senyum tipis atau setidaknya mengangguk sambil bilang, “Iya, gue ngerti nih.”