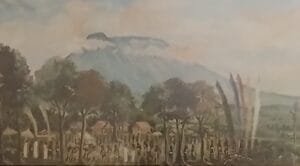Vakansiinfo – Wayang golek bukan sekadar boneka kayu yang dimainkan dalam sebuah pementasan. Ia adalah wujud nyata dari kebudayaan yang hidup, berkembang, dan terus bertahan lintas generasi. Kehadirannya mengakar dalam sejarah panjang tradisi Nusantara, terutama di tanah Sunda, sebagai media hiburan, pendidikan, hingga penyebaran nilai-nilai luhur.
Asal-Usul Wayang Golek: Dari Kulit Menuju Kayu
Asal mula wayang golek memang tidak tercatat secara pasti. Namun, banyak sejarawan dan budayawan sepakat bahwa wayang golek adalah bentuk evolusi dari wayang kulit. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Sunan Kudus yang, menurut Salmun (1986), pada tahun 1583 menciptakan wayang dari kayu yang dapat di mainkan pada siang hari—di kenal kemudian sebagai wayang golek.
Ismunandar (1988) mencatat bahwa Sunan Kudus membuat 70 buah wayang purwa dengan cerita Menak yang diiringi gamelan Salendro. Karena tidak menggunakan kelir dan menyerupai boneka, bentuknya yang menyerupai golek (berputar) inilah yang memberi nama wayang golek.
Di daerah Cirebon, wayang ini dikenal sebagai wayang golek papak atau cepak, dengan ciri kepala datar. Pada masa Pangeran Girilaya (1650–1662), lakon yang dibawakan berkembang mencakup cerita sejarah dan babad tanah Jawa, terutama yang berfokus pada penyebaran Islam.
Pada awal abad ke-19, Dalem Karang Anyar memerintahkan Ki Darman, seorang ahli wayang kulit dari Tegal, untuk menciptakan wayang dari kayu. Hasilnya adalah wayang gepeng yang kemudian berkembang menjadi wayang golek membulat seperti yang kita kenal sekarang. Penyebarannya di tanah Priangan diperkuat oleh pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan pantai utara dengan dataran tinggi.
Jenis-Jenis Wayang Golek
Wayang golek berkembang menjadi tiga jenis utama:
- Wayang Golek Cepak (Papak): Berasal dari Cirebon, dengan cerita yang berkisar pada babad dan legenda lokal, menggunakan bahasa Cirebon.
- Wayang Golek Purwa: Membawakan kisah Ramayana dan Mahabharata dalam bahasa Sunda, paling banyak di kenal di daerah Sunda.
- Wayang Golek Modern: Menggabungkan cerita tradisional dengan teknik pertunjukan modern seperti penggunaan listrik untuk efek visual. Di kembangkan oleh R.U. Partasuanda dan Asep Sunandar pada tahun 1970-an hingga 1980-an.
Proses Pembuatan: Seni di Balik Kayu
Wayang golek di buat dari kayu albasiah atau lame. Prosesnya melibatkan keterampilan tinggi dalam mengukir dan meraut hingga menyerupai karakter tertentu. Pewarnaan menjadi elemen penting untuk memperkuat karakter tokoh, dengan cat duko di gunakan untuk menghasilkan warna-warna cerah. Warna dasar seperti merah, putih, prada, dan hitam memiliki makna simbolis dalam menggambarkan sifat tokoh.
Nilai Budaya: Cermin Etika dan Pendidikan
Wayang golek tidak hanya berperan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan penyebaran nilai-nilai budaya. Para dalang sebagai tokoh sentral pertunjukan memiliki tanggung jawab moral yang terangkum dalam “Sapta Sila Kehormatan Seniman Seniwati Pedalangan Jawa Barat”, yang di susun pada 28 Februari 1964. Kode etik ini menekankan pentingnya etika, pendidikan masyarakat, patriotisme, dan pelestarian budaya dalam praktik kesenian pedalangan.
Wayang golek adalah warisan budaya yang unik dan bermakna. Ia bukan sekadar boneka kayu, tetapi representasi dari nilai, sejarah, dan jati diri bangsa. Dalam balutan cerita-cerita klasik maupun kontemporer, wayang golek terus memainkan peran penting sebagai penjaga budaya Nusantara, sekaligus pengingat bahwa dalam kayu yang diam pun, dapat hidup semangat sebuah peradaban.
(Fai)